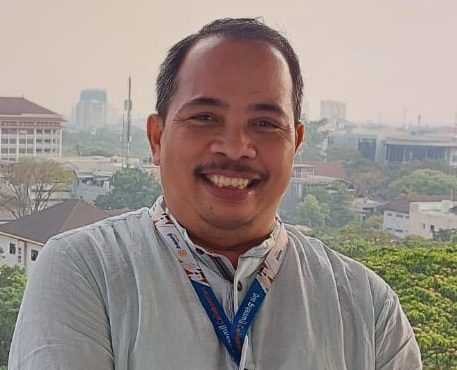Ketika Kiai Bertemu Algoritma Media : Refleksi Hari Santri di Era Krisis Otoritas Pengetahuan
Ketika Kiai Bertemu Algoritma Media : Refleksi Hari Santri di Era Krisis Otoritas Pengetahuan

Oleh :
M Kh Rachman Ridhatullah (Santri Kalong Pondok Pesantren Annizhom, Tanjung Priok, Jakarta Utara 1984-1988)
Beberapa hari menjelang Hari Santri Nasional, jagat maya Indonesia diramaikan oleh kabar yang terasa getir: perseteruan antara salah satu stasiun televisi nasional, Trans7, dan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Tayangan sebuah program dianggap melecehkan martabat pesantren dan kiai pengasuhnya. Reaksi publik pun meledak. Santri, alumni, dan masyarakat bereaksi; media sosial bergolak, regulator turun tangan, manajemen Trans7 meminta maaf.
NAMUN-– di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar soal etika penyiaran. Ini bukan semata persoalan “salah tayang”. Ia adalah cermin zaman — tanda bahwa kita sedang menghadapi pergeseran besar dalam otoritas pengetahuan: dari kiai ke algoritma media, dari nilai ke viralitas, dari kesantunan ke performa.
Pesantren dan Bayang-Bayang Zaman
Dalam sejarah panjangnya, pesantren adalah menara ilmu dan moral bangsa. Di bawah atapnya yang sederhana, ilmu diwariskan bukan sekadar lewat teks, tapi lewat teladan; bukan lewat suara keras, tapi kesabaran yang dalam. Kiai menjadi penjaga moral, guru kehidupan, dan rujukan sosial. Ia dihormati bukan karena kekayaan atau kuasa, tapi karena barakah ilmunya — energi spiritual yang tumbuh dari keikhlasan dan kedalaman.
Namun kini, dunia telah berubah. Pengetahuan tidak lagi menunggu petuah di serambi masjid, melainkan muncul di layar ponsel. Sanad keilmuan tergantikan oleh tautan digital; tafsir kebenaran diatur bukan oleh hikmah, tapi oleh algoritma media. Dalam lanskap seperti itu, kiai tidak lagi menjadi satu-satunya sumber otoritas. Media dan mesin telah mengambil sebagian perannya — mengubah cara manusia mempercayai sesuatu.
Kita hidup di zaman yang disebut sosiolog Zygmunt Bauman sebagai liquid modernity — dunia yang cair, di mana nilai dan makna mudah larut oleh kecepatan. Di dalamnya, pesantren berjuang mempertahankan kedalaman di tengah laju informasi yang menuntut serba cepat. Sedang kiai berhadapan dengan lawan tak berwajah: sistem digital yang memproduksi pengaruh tanpa moral, dan kepastian tanpa kedalaman.
Benturan Dua Dunia: Dari Serambi Pesantren ke Ruang Siar
Kasus Trans-7 dan Lirboyo menjadi panggung nyata dari benturan dua logika: logika nilai di pesantren dan logika algoritma media. Logika nilai dibangun di atas penghormatan, adab, dan konteks. Ia percaya bahwa setiap kata memiliki beban moral; bahwa ilmu bukan sekadar data, tapi amanah. Sementara logika algoritma media bekerja dengan hukum dingin: apa yang mengundang klik, itulah yang layak tayang. Dalam sistem ini, yang viral lebih penting daripada yang benar, yang menarik lebih diutamakan daripada yang bermartabat.
Maka ketika pesantren — institusi yang berdiri di atas etika dan spiritualitas — bertemu dengan dunia media yang diatur oleh mesin statistik, benturan itu nyaris tak terelakkan. Kiai, yang terbiasa menjadi sumber makna, kini menjadi subjek konten. Pesantren, yang selama ini menjadi ruang sakral pendidikan jiwa, tereduksi menjadi latar eksotisme dalam program televisi.
Itulah sebabnya reaksi keras masyarakat bukan hanya soal harga diri Lirboyo, tapi soal perasaan kolektif bahwa sesuatu sedang bergeser dari akarnya. Ada luka simbolik ketika lembaga moral bangsa disalahpahami oleh media yang seharusnya mengedukasi publik. Di situ, yang dipertaruhkan bukan nama baik satu pesantren, melainkan martabat kesantrian sebagai ruang nilai.
Kiai, Algoritma, dan Krisis Epistemik
Secara sosiologis, kita sedang hidup di tengah krisis epistemik — krisis tentang siapa yang layak dipercaya. Dulu, otoritas ilmu ditentukan oleh sanad, oleh guru, oleh proses panjang. Kini, otoritas dibentuk oleh sistem rekomendasi: siapa yang sering muncul di beranda, dialah “guru baru”. Kebenaran bergeser dari yang bersumber pada hikmah menjadi yang bersumber pada trending topic.
Inilah bentuk baru dari kekuasaan pengetahuan yang dulu diperingatkan oleh Michel Foucault: kebenaran tidak lagi diatur oleh nilai, tetapi oleh sistem. Dan dalam dunia digital, sistem itu bernama algoritma media. Ia bekerja senyap, mengatur persepsi publik, membentuk selera, bahkan menentukan siapa yang didengar dan siapa yang dilupakan.
Bagi pesantren, tantangan ini bukan sekadar teknologi, tetapi eksistensial. Bagaimana menjaga keaslian pengetahuan dan adab dalam dunia yang menilai segalanya berdasarkan jumlah penonton? Bagaimana menanamkan kedalaman di tengah budaya yang menuntut kecepatan?
Hari Santri: Dari Seremoni ke Refleksi
Hari Santri Nasional seharusnya bukan sekadar upacara dengan sorban dan bendera, melainkan momen reflektif untuk membaca ulang posisi santri di tengah revolusi digital. Santri tidak boleh puas hanya menjadi “pewaris masa lalu”, tapi harus tampil sebagai “penafsir masa kini”.
Mereka perlu menyelami dua samudra: samudra kitab dan samudra data.
Menghafal alfiyah tanpa memahami algoritma hanya akan menjadikan mereka penjaga nostalgia; tapi memahami teknologi tanpa menegakkan adab hanya akan menjadikan mereka budak zaman.
Pesantren perlu bertransformasi dari sekadar pusat transmisi ilmu menjadi pusat literasi moral digital. Santri bukan hanya belajar tafsir kitab, tetapi juga belajar menafsir media. Kiai tidak cukup menjadi pendidik ruhani, tapi juga kurator informasi — menuntun umat agar tidak tersesat di lautan data.
Belajar dari Lirboyo dan Trans-7: Jalan Tengah yang Mendidik
Dari peristiwa Lirboyo–Trans-7, kita belajar dua hal penting. Pertama, bahwa dunia digital tidak mengenal kekebalan simbolik: bahkan lembaga sekuat pesantren pun bisa disalahpahami jika tidak berkomunikasi dengan cara yang sesuai zaman. Karena itu, pesantren perlu mengembangkan literasi media dan mekanisme komunikasi publik. Unit humas pesantren, pelatihan media bagi kiai muda, dan kurikulum literasi digital bagi santri adalah langkah strategis yang mendesak.
Kedua, bahwa media massa juga harus belajar kembali tentang etika representasi nilai. Rating bukan pembenaran atas kekeliruan. Program televisi yang mengangkat tema keagamaan harus memahami sensitivitas budaya dan spiritual umat. Jika media ingin menjadi cermin masyarakat, maka cermin itu harus bersih dari bias sensasional dan menghormati ruang-ruang sakral seperti pesantren.
Permintaan maaf Trans7 kepada Lirboyo patut diapresiasi, tapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pergeseran kesadaran: dari logika viral menuju logika hormat; dari kejar rating menuju pencarian makna.
Epilog
Barangkali inilah tantangan zaman yang sebenarnya: menjadi manusia yang tetap punya nurani di tengah dunia yang dikuasai mesin. Kiai dan algoritma media boleh berbeda, tapi keduanya berbicara pada manusia yang sama: yang sedang mencari makna.
Hari Santri kali ini mestinya menjadi ajang perenungan nasional: mampukah kita menjaga ruh ilmu di tengah kebisingan data? Mampukah pesantren tetap menjadi pusat moral di tengah pusaran teknologi yang netral terhadap etika?
Pesantren lahir dari kesunyian, bukan dari keramaian. Dari adab, bukan dari debat. Maka tugas kita bukan sekadar membela pesantren ketika disalahpahami, tapi meneguhkan kembali bahwa ia adalah rumah makna — tempat di mana ilmu tidak pernah kehilangan hati.
Dan mungkin, di era ketika algoritma media menulis ulang dunia, satu-satunya cara untuk bertahan adalah menulis ulang hati dengan ilmu, dan menulis ulang ilmu dengan akhlak.** Penulis dosen dan bertempat tinggal di Kota Bandung